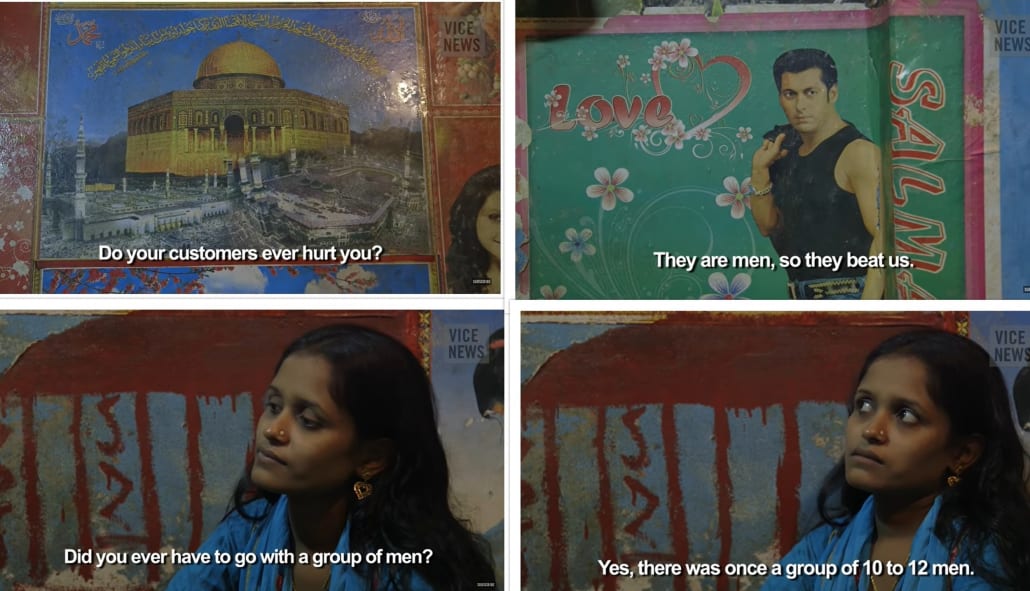Konsumsi Makna Zero Waste di Kalangan Anak Muda
Oleh: Manggiasih Tilotama Tunjung Biru
Belakangan, sampah plastik dianggap sebagai isu yang sangat krusial bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan mengangkat slogan zero waste, gerakan mengurangi sampah plastik mulai digalakkan dan kian hari kian diminati terutama di kalangan anak muda. Di berbagai toko dan pusat perbelanjaan kemudian sering ditemui barang-barang alternatif pengganti plastik, seperti penjualan sedotan besi atau sedotan berbahan dasar organik yang banyak diminati anak muda. Tak terelakkan, gaya hidup zero waste menjadi budaya pop yang kemudian mengalami komodifikasi oleh sistem kapitalisme. Sehingga gerakan go green direduksi maknanya, bukan sebagai gerakan untuk memelihara keberlanjutan lingkungan hidup, namun semata-mata menjadi tren baru dalam budaya konsumsi.
Manariknya, anak muda sangat dekat dengan tren konsumsi barang-barang tertentu, seperti tren mengonsumsi aneka varian kopi saat bekerja atau mengerjakan tugas. Sebenarnya, tidak menjadi masalah jika kita tidak mengonsumsi kopi yang dijual dengan harga tinggi di kafe-kafe yang sedang menjamur di perkotaan. Namun disadari atau tidak, kapitalisme mampu membangun hiperrealitas atas konsumsi meminum kopi, bahwa identitas “muda” lekat dengan budaya minum kopi dengan standar pengolahan dan pengemasan tertentu. Anak muda dan tren konsumsi kopi menjadi salah satu contoh bahwa budaya konsumsi dikonstruksi oleh kepitalisme yang dalam hal ini salah satu sasarannya adalah anak muda.
Tren kemudian berubah menjadi tren minum kopi dengan semangat zero waste. Banyak kedai kopi yang menawarkan alternatif bagi konsumennya untuk membawa tumblr sendiri ketika membeli kopi. Beberapa kedai juga menyediakan sedotan berbahan dasar besi yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan sedotan plastik. Tak hanya itu, beberapa kedai kopi bahkan menjual tumblr dan sedotan plastik dengan tawaran para pembeli mampu mendukung gerakan zero waste. Maka dapat dikatakan bahwa ada perubahan tren, dimana untuk menjadi pemuda yang zero waste, kita diharuskan untuk mengonsumsi produk-produk yang mengusung tema zero waste.
Pertanyaannya kemudian adalah, sebenarnya apa yang dikonsumsi oleh anak muda? Dalam contoh tren minum kopi, apakah anak muda mengonsumsi kopi atau mengonsumsi makna lain dari meminum kopi? Lalu dalam konteks zero waste yang juga dekat dengan bisnis kuliner, apakah konsep mengenai keberlanjutan lingkungan hidup disadari betul oleh anak muda yang seringkali turut mengampanyekan gerakan zero waste?
Baudrillard dalam Haryatmoko (2016) memperkenalkan konsep Simulacra yang menjelaskan diskursus mengenai realitas, simbol, dan masyarakat. Bagi Baudrillard, masyarakat postmodern sudah hidup dalam dunia yang penuh dengan simbol. Komoditas tidak lagi dihargai dengan nilai guna yang nyata, melainkan sudah digantikan dengan kode, simbol, dan hiperrealitas. Dalam sistem kapitalisme, hubungan antar-objek dikontrol oleh kode atau tanda. Sehingga dalam masyarakat konsumsi, aktivitas konsumsi tidak lagi pada nilai guna dari komoditas, melainkan konsumsi tanda. Tanda-tanda dalam masyarakat post-modern tidak dimaknai memiliki nilai-nilai yang setara, melainkan dimaknai sesuai dengan aturan dalam sebuah hirarki. Sehingga konsumsi tanda dapat menjadi penentu kelas sosial.
Tren konsumsi produk, baik pangan atau pun perabotan sehari-hari yang mengusung konsep zero waste yang marak di kalangan anak muda menunjukkan bahwa ada makna yang ingin dikonsumsi oleh anak muda ketika membeli suatu produk yang membuatnya diakui sebagai anak muda “kekinian” yang peduli terhadap isu lingkungan. Sikap peduli terhadap isu lingkungan direduksi menjadi sesempit praktik konsumsi terhadap produk-produk zero waste. Dalam konteks ini konsumsi pangan atau perabotan sehari-hari tidak lagi didasarkan pada nilai gunanya, melainkan didasarkan semangat zero waste yang bahkan sudah direduksi maknanya.
Merefleksikan dari uraian di atas, semangat melindungi alam untuk keberlanjutan lingkungan hidup kini telah banyak berubah maknanya. Pelestarian lingkungan tidak lagi diimplementasikan melalui hal-hal sesederhana membawa bekal dari rumah, merebus air minum agar tidak perlu membeli air mineral, menanam pohon atau bentuk aktivisme-aktivisme kolektif seperti penolakan terhadap pembangunan yang merusak ekosistem. Namun, ada tren di kalangan anak muda dimana menjaga keberlanjutan lingkungan hidup diimplementasikan dengan konsumsi produk-produk yang mengampanyekan zero waste dengan harga yang tidak mampu dijangkau oleh semua kalangan.
Referensi:
Haryatmoko. 2016. Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-strukturalis. Yogyakarta: Kanisius.