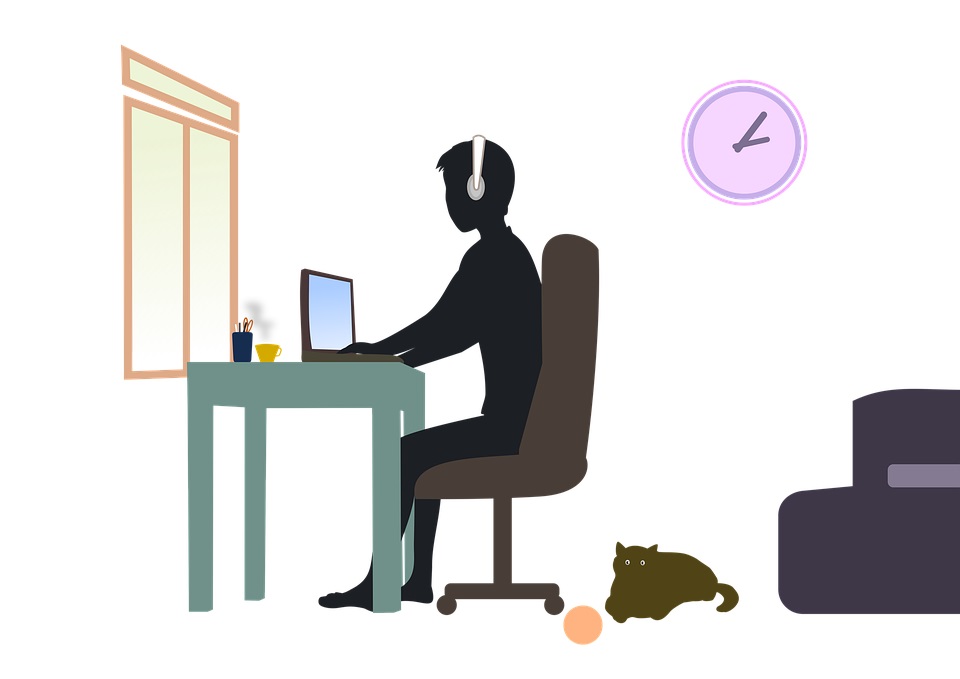Oleh: Arya Malik
Mungkin sudah menjadi perbincangan yang banal hari ini, tentang bagaimana kerusakan alam dan pelestarian lingkungan hidup. Gerakan dan aktivisme untuk melestarikan lingkungan, menjadi agenda penting yang dengan beragam cara dilakukan untuk membangun kepedulian terhadap alam dan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan iklim adalah problema nyata yang suatu saat akan dihadapi. Isu ini mulai membumi ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali perempuan, yang ikut berkontribusi dalam agenda-agenda tersebut, salah satunya adalah Greta Thunberg. Beberapa dari kita mungkin sudah tidak asing dengannya, seorang perempuan muda yang muncul kehadapan publik untuk menyuarakan perlawanan terhadap kerusakan alam. Thunberg mulai dikenal ketika menggelar demo terkait perubahan iklim di Stockholm pada Agustus 2018 lalu, ia mencetuskan gerakan bolos sekolah untuk menyuarakan tentang perubahan iklim. Ia berdiri di depan gedung parlemen dan memegang sebuah tanda bertuliskan “skolstrejk for klimatet,” atau “mogok sekolah demi iklim”. Thunberg saat itu masih berusia 15 tahun, saat memilih bolos sekolah hingga pelaksanaan pemilu Swedia pada 9 September 2018. Saat itu Swedia mengalami musim panas terparah dalam 262 tahun terakhir karena gelombang panas disertai kebakaran hutan, dan Thunberg menuntut pemerintah Swedia untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan kesepakatan Paris.
Melalui perjuangannya, yang kemudian viral di media sosial, masyarakat dunia mulai aware terhadap dampak dari kerusakan lingkungan, seperti pemansan global, perubahan iklim, pencemaran air dan udara, serta dampak-dampak lain yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Tidak sedikit yang terinspirasi oleh Thunberg, dan tergerak untuk turut serta menjaga lingkungan. Banyak dukungan yang diberikan kepadanya, Thunberg juga mendapat beberapa penghargaan untuk kontribusinya terhadap gerakan pelestarian lingkungan, dan masuk nominasi penghargaan Nobel. Thunberg mungkin menjadi ikon bagaimana kaum muda peduli terhadap kerusakan lingkungan. Berbagai kesempatan berbicara di muka dunia, dilakukan Thunberg dengan berapi-api, salah satu yang terkenal saat ia menyuarakan isu kerusakan lingkungan pada konferensi PBB di New York, dengan kutipannya yang terkenal
“….This is all wrong. I should not be up here. I should be back in school on the other side of the ocean, yet you all come to us young people for hope. How dare you! You have stollen my dream and my childhood with your empty words and yet i am one of the lucky ones…“,
ia mengecam para pemimpin dunia, yang merupakan orang dewasa, karena telah membiarkan kerusakan lingkungan terjadi. Realita masa kanak-kanaknya dengan alam yang tercemar, dan kekhawatirannya akan masa depan bumi yang layak untuk makhluk hidup, menjadi konsern Thunberg dalam perjuangannya.
Sepak terjang Thunberg menjadi salah satu fenomena yang menarik dalam diskursus mengenai perjuangan perempuan dan lingkungan. Tapi, bagaimana bila lingkup pembahasannya kita letakan pada konteks lain, bisa jadi terdapat perbedaan dari bagaimana isu ini bergulir dan bekerja. Seperti dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai perjuangan perempuan dan lingkungan telah banyak terjadi di berbagai daerah. Beberapa waktu silam, terjadi perlawanan yang dilakukan oleh petani-petani perempuan Desa Sukamulya, terhadap aparat pemerintah yang ingin menggusur lahan mereka untuk pembangunan Bandara di Kabupaten Majalengka, atau yang belum lama ini juga terjadi, perlawanan kelompok petani di Kulon Progo, di mana para petani perempuan ikut hadir dan merapatkan barisan, saat terjadi penggusuran lahan mereka yang akan dibuat bandara. Perlawanan kelompok petani di Kendeng juga menjadi salah satu contoh, bagaimana perempuan terlibat dalam perjuangan terhadap eksploitasi lingkungan, mereka menolak berdirinya pabrik semen di lingkungan mereka, karena berpotensi mencemari lingkungan dan merusak lahan produktif pertanian. Dalam babak sejarah Indonesia di masa Hindia Belanda pun, perlawanan perempuan dan lingkungan juga tercatat dalam peristiwa perlawanan petani-petani perempuan di Garut terhadap pemerintah kolonial pada tahun 1919, yang dikenal dengan Peristiwa Cimareme.
Di Indonesia, aksi perlawanan perempuan cenderung terjadi di rural area dan tidak teroganisir, bahkan terjadi secara spontan. Dalam beberapa kasus, mereka juga menggunakan tubuhnya sebagai barikade saat berhadapan dengan aparat. Apa yang mereka perjuangkan berhubungan dengan ‘place’, para petani perempuan itu protes karena apa yang mereka perjuangkan menyangkut dengan urusan place atau ‘ruang mukim’ yang mereka hidupi. Ruang mukim sangat penting bagi mereka untuk memperoleh sumber nafkah, dan sekaligus menjalankan reproduksi sosial. Konsep ruang mukim, menempatkan kegiatan mencari nafkah yang sekaligus menyediakan pangan, mengurus semua kebutuhan rumah tangga, mengurus anggota keluarganya, merawat lingkungan, dan merawat relasi-relasi sosial dalam berbagai wujudnya. Sehingga ‘ruang mukim’ ini menjadi sesuatu yang terus hidup dan dihidupi.
Bertolak dari pembahasan ini, perlu disadari bahwa paradoks adalah sebuah keniscayaan, begitu juga dalam ranah-ranah perjuangan, apa yang terlintas dibenak kita saat merespon perjuangan Thunberg? Sebaliknya, bagaimana dengan perjuangan kaum petani perempuan? Mungkin terdapat perbedaan narasi antar Thunberg dengan petani perempuan di atas. Pemahaman terhadap perbedaan ini dapat kita gunakan untuk melihat paradoks yang muncul. Narasi yang hadir dalam perjuangan Thunberg mungkin adalah yang paling banyak direproduksi hari ini, sedangkan, narasi perjuangan para petani perempuan, cenderung direproduksi secara sporadis karena minim terekspos. Padahal, bukankah di saat mereka menjadi perempuan yang mempertahankan ruang mukimnya, mereka juga menjadi front tier dalam menghadapi kerusakan lingkungan? Walaupun, mungkin terdapat perbedaan yang melatarbelakangi perjuangan mereka, di mana petani perempuan cenderung berbasis materil seperti lahan dan properti, sedangkan Thunberg memperjuangkan masa depannya dengan bumi yang asri. Ketimpangan kelas adalah salah satu faktor yang menyebabkan problema ini. Pihak-pihak yang ditentang adalah elit-elit yang memiliki privilese lebih dalam tatanan masyarakat, elit pejabat, korporasi, pemilik modal, atau pihak-pihak lain yang mendapat keuntungan dari eksploitasi lingkungan ini. Hal ini dapat menjadi benang merah yang menghubungkan narasi perjuangan mereka.
Sebagai generasi muda, narasi tersebut dapat kita jadikan refleksi bagi diri kita masing-masing. Khususnya, terhadap masa depan kita, di mana kita berhak memiliki ruang mukim, kita berhak atas kehidupan yang sejahtera, kita berhak atas lingkungan yang asri, kita berhak menuntut dampak yang hadir dari pihak-pihak tersebut. Perlawanan yang dilakukan, entah oleh Thunberg, para petani perempuan, atau dalam lingkup lainnya yang lebih luas, dapat kita maknai dalam satu frame yang utuh sebagai narasi perjuangan terhadap ketimpangan kelas. Paradoks yang muncul perlu kita pahami dengan cermat dan kita sikapi secara bijak, agar nafas pejuangan dapat berhembus secara inklusif.