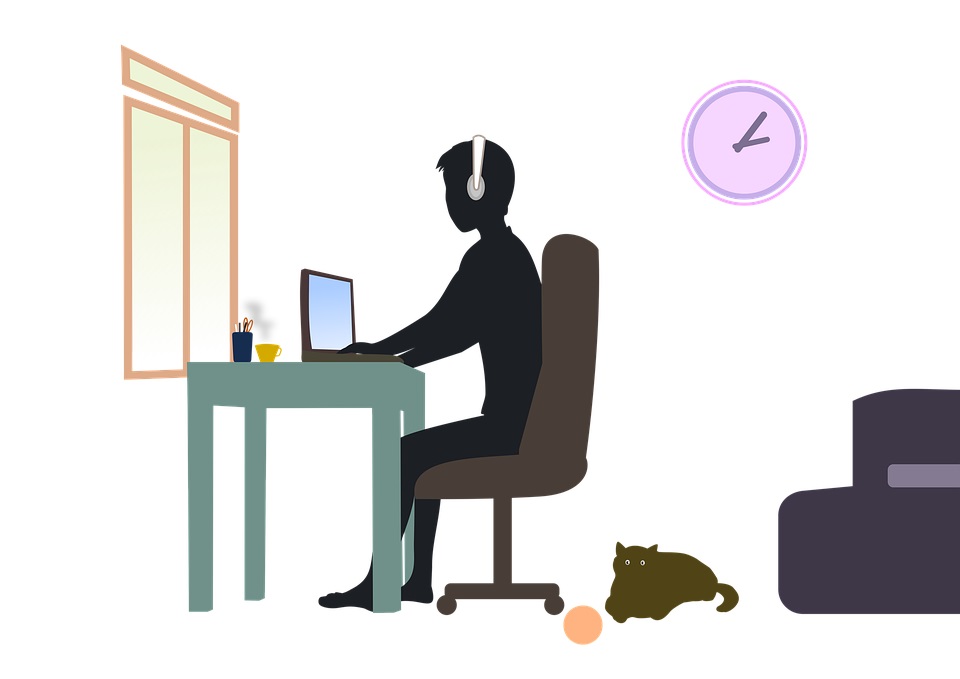Pandemi dan Resiko Pekerja Muda
Oleh: Arya Malik
Pandemi yang melanda membuat kehidupan pekerjaan mengalami kendala, munculnya kebijakan PSBB mengakibatkan banyak perusahaan tidak dapat berjalan dengan produktif. Penerapan sistem WFH (work from home) menjadi cara yang diambil banyak perusahaan dalam menghadapi pandemi. Akan tetapi, terdapat beberapa sektor yang tidak bisa menerapkan sistem tersebut, sehingga banyak juga pekerja yang dirumahkan karena perusahaan tidak mendapat pemasukan, atau bahkan merugi. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang terkena dampak akibat kondisi selama pandemi.
“Sebelumnya saya bekerja sebagai salah satu pekerja di sektor wisata yang ada di Yogyakarta. Setelah ada pandemi ini, saya di rumahkan, dan pekerjaan saya saat ini berkebun dan menjual hasil-hasil berkebun.”-Titis
Di sisi lain, sebagian pelaku usaha merumahkan para pekerjanya dengan dalih pandemi. Merumahkan karyawan menjadi cara menekan kerugian akibat pandemi, namun seringkali perusahaan tidak membekali para pekerja dengan skill, kompensasi, ataupun perlindungan selama pandemi. Pemerintah juga cenderung abai, karena tidak memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan dan keamanan yang layak bagi para pekerja. Seharusnya kondisi ini menjadi tanggungjawab semua pihak, khususnya pengusaha dan pemerintah.
“Kondisinya sekarang lagi parah, banyak perusahaan-perusahaan yang lagi kolaps, sehingga banyak yang di rumahkan. Tapi juga ada banyak perusahaan yang menggunakan pandemi ini sebagai alat untuk merumahkan dan mem-phk-an karyawannya. Dirumahkan itu adalah metode paling ampuh, saat ini, untuk mem-phk orang tanpa pesangon. Padahal berdasarkan undang-undangnya, pihak yang memutus kontrak kerja wajib membayar biaya penalty sesuai kontrak kerja. Tapi karena kondisi pandemi, jadi banyak perusahaan yang tidak membayar pesangon…Perusahaan-perusahaan, itu bertanggungjawab untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari para buruhnya. Sementara pemerintah, itu bertanggungjawab untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk para buruh yang keluar dari pekerjaannya.”-Dani
Semua pihak, terutama pemerintah dan para pengusaha, harus peduli dengan nasib pekerja muda. Perusahaan seharusnya dapat memberikan pelatihan pengembangan SDM agar dapat menguasai skill di luar lingkup pekerjaan mereka. Pemerintah, jugas seharusnya bertanggungjaawb untuk memberi jaminan atas perlindungan hak-hak para pekerja, terutama di masa kritis seperti masa pandemi.
Sejauh ini, pandemi telah berdampak pada banyak sektor dalam konteks perekonomian dan ketengakerjaan. Dilema tentang bagaimana kedepannya nasib para pekerja, mencakup pertanyaan besar, apakah harus diam dan menunggu, atau perlu memulai dengan serangkaian perubahan.
“kalo untuk wait and see, sepertinya sudah terlalu lama. Tapi untuk memulai lagi, pasti akan ada perubahan. Seperti di tempat saya, tempat wisata, itu pasti perlu tambahan pegawai, sementara untuk penambahan pegawai, itu butuh training dan itu takes time.”-Titis
Pada kenyataannya, untuk memulai kembali kegiatan perekonomian, para pengusaha juga dihadapkan dengan perubahan akibat pandemi. Besar kemungkinan, akan terjadi peningkatan pengeluaran dalam operasional mereka. Sedangkan pemasukan yang didapat, kemungkinan akan menurun. Hal ini menjadi resiko yang akan dihadapi para pelaku usaha dan juga para pekerja.
“perusahaan harus nambah cost kalo mau nambah karyawan, dan profit margin perusahaan itu pasti akan turun. kemungkinan besar temen-temen buruh juga harus siap nerima gaji yang lebih kecil, mungkin bisa lebih kecil dari UMR.”-Dani
Pada titik ini, di mana kesulitan sedang menimpa baik para pekerja maupun para pengusaha, kehadiran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk menjamin kehidupan masyarakatnya. Namun, kecenderungan yang ada, pemerintah justru abai dan membiarkan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang harus mereka hadapi sendirian.
“mau gamau pemerintah harusnya turun tangan, karena masyarakat butuh mereka. tapi kebiasaan pemerintah itu kan hanya dateng saat kampanye. pemerintah itu harusnya hadir, untuk membekali, atau kayak memberikan blt. tapi pemerintah sendiri ga ngerti gimana situasinya, datanya kacau, mereka tidak mau mengakui kalo data mereka itu kacau. kondisinya mereka bingung, akhirnya buruh dan pengusaha dibiarkan, rakyat dibiarkan.”-Dani
Masih banyak yang perlu dibenahi, terutama pemerintah. Karena sejauh ini skenario tanggap darurat selama pandemi, masih memiliki banyak kekurangan. Padahal, besar kemungkinan di masa yang akan datang, kondisi-kondisi serupa dapat terjadi lagi. Pemerintah seharusnya memiliki skenario yang berpihak kepada rakyatnya. Sedangkan masyarakat, juga tidak bisa terus bergantung kepada pemerintah, karena masih banyak yang perlu dibenahi dari pemerintah. Masyarakat perlu memiliki kesadaran tentang pentingnya kedaulatan ekonomi secara pribadi. Kemampuan-kemampuan unik yang bisa menunjang kehidupan dalam kondisi darurat, seperti pandemi saat ini, sangat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi.